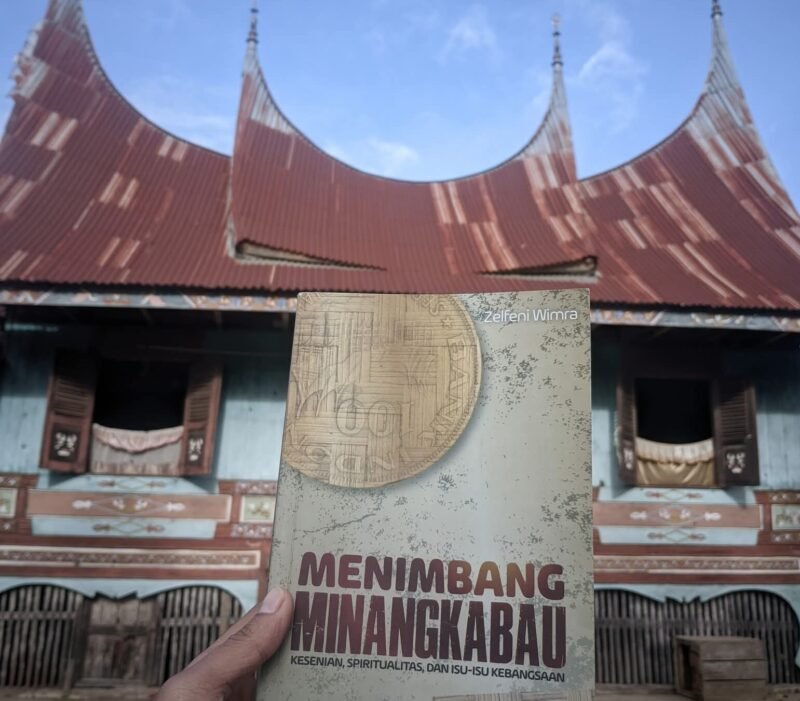Ia menjadi Bundo Kanduang dalam semesta kecil saya.
Kekuasaan matrilineal ini, di era digital, menemukan wujud barunya. Setidaknya dua kali seminggu, saya akan melakukan panggilan video.
Di hadapan layar gawai, saya akan mempresentasikan semua rencana hidup seolah sedang sidang di hadapan dewan penguji skripsi.
Setiap langkah, setiap rencana, sebisa mungkin mendapat persetujuannya.
Bukan karena takut, melainkan karena restu dan doanya adalah kompas yang memberi saya keyakinan untuk melangkah.
Tanpa persetujuannya, rasanya setiap rencana terasa rapuh.
Saya pernah mengabaikan getaran itu sekali, dan pelajarannya membekas seumur hidup.
Suatu waktu, saya hendak berpakansi bersama kawan-kawan pondok.
Ibu menunjukkan berat hati untuk melepas saya pergi, namun ayah—dengan logika seorang bapak—memberi izin.
Saya memilih untuk tetap berangkat. Tragedi kecil pun terjadi, dan saya hampir kehilangan kelingking kaki.
Saya tidak pernah menyalahkan ayah. Saya menyalahkan diri sendiri yang gagal menangkap sinyal kekhawatiran dari perempuan yang melahirkan saya.
Saat itu saya belajar: logika seorang ayah memang menenangkan, tetapi getaran batin seorang ibu adalah perlindungan.
Perlindungan tak kasat mata itulah yang kemudian menuntun saya pada sebuah perenungan yang lebih dalam.
Saya mulai memetakan kaitan antara kekuatan batin ibu saya dengan struktur besar yang menaungi kami.
Dari sanalah saya memahami bahwa pengaruh sistem matrilinial Minangkabau jauh melampaui urusan warisan atau nama suku.
Ia menyusup hingga ke ruang paling privat seorang laki-laki: ruang batin dan pengambilan keputusan.
Perempuan, khususnya ibu, tidak hanya menjadi Limpapeh Rumah Nan Gadang yang menjaga marwah keluarga di ranah publik.