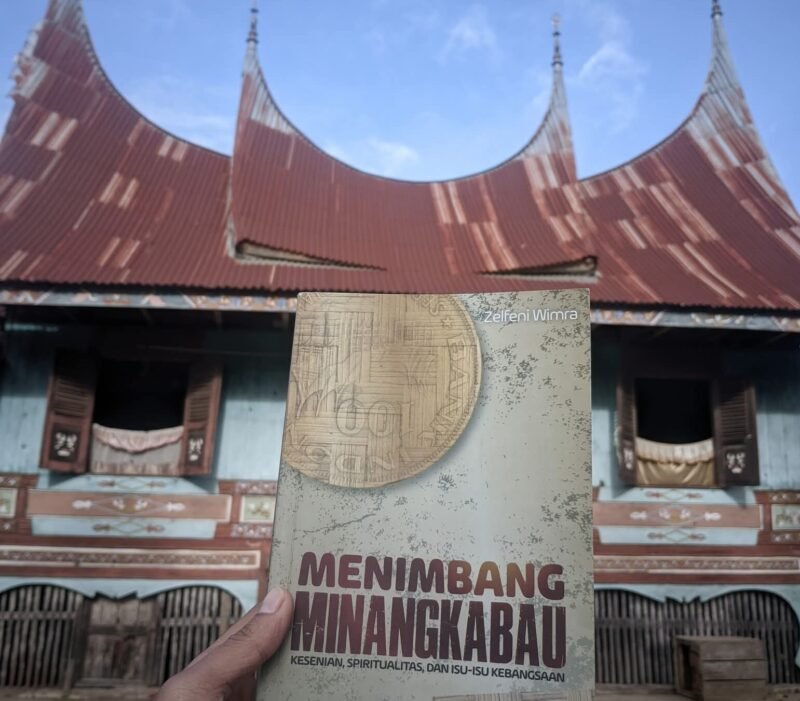ESAI BUDAYA
OLEH GERI SEPTIAN
Dahulu, hal pertama yang saya cari setiap kali pulang dari pondok pada setiap hari Kamis bukanlah kursi untuk melepas lelah, melainkan sosok ibu.
Jika kebetulan ayah yang menyambut di pintu, pertanyaan pertama yang meluncur dari bibir saya bukanlah tentang kabarnya, melainkan, “Di mana Ama, Pa?”
Bahkan saat dering telepon diangkat oleh suara Apa, pertanyaan refleks saya tetap sama, “Ma ama, Pa?”
Ada kekosongan yang terasa janggal jika wajahnya belum tertangkap oleh pandangan saya.
Pertanyaan sederhana itu, kini saya sadari, bukanlah sekadar kebiasaan seorang anak manja.
Ia adalah manifestasi terdalam dari sebuah dunia yang membesarkan saya.
Saya lahir dan ditempa dalam lingkungan matrilineal yang pekat.
Masa kecil saya berada dalam asuhan almarhumah nenek, diawasi oleh para tante, dan dikontrol sepenuhnya oleh Ama.
Ruang dengar saya dipenuhi obrolan sore para uwo-uwo—tentang ekonomi yang mampet, jerat rentenir, hingga cita-cita sederhana untuk bisa kembali salat berjamaah di surau.
Tiga guru ngaji saya, semuanya perempuan. Dari delapan belas guru di sekolah dasar, hanya dua yang laki-laki.
Kurang matrilineal apa lagi hidup saya? Sistem ini bukan lagi sekadar adat, ia adalah udara yang saya hirup.
Berpulangnya nenek ke pangkuan Tuhan menjadi titik balik emosional saya.
Peran sentral itu tidak pernah benar-benar kosong; ia diwariskan, dialihkan, dan disempurnakan oleh ibu.
Ibu menjadi pengganti dalam semua hal: tumpuan kasih sayang, tempat berkeluh kesah, hingga pemegang mandat tradisi di ruang publik.
Beliaulah yang memandu langkah dalam prosesi adat seperti baralek, manjanguak, atau manyilau urang takuruang.