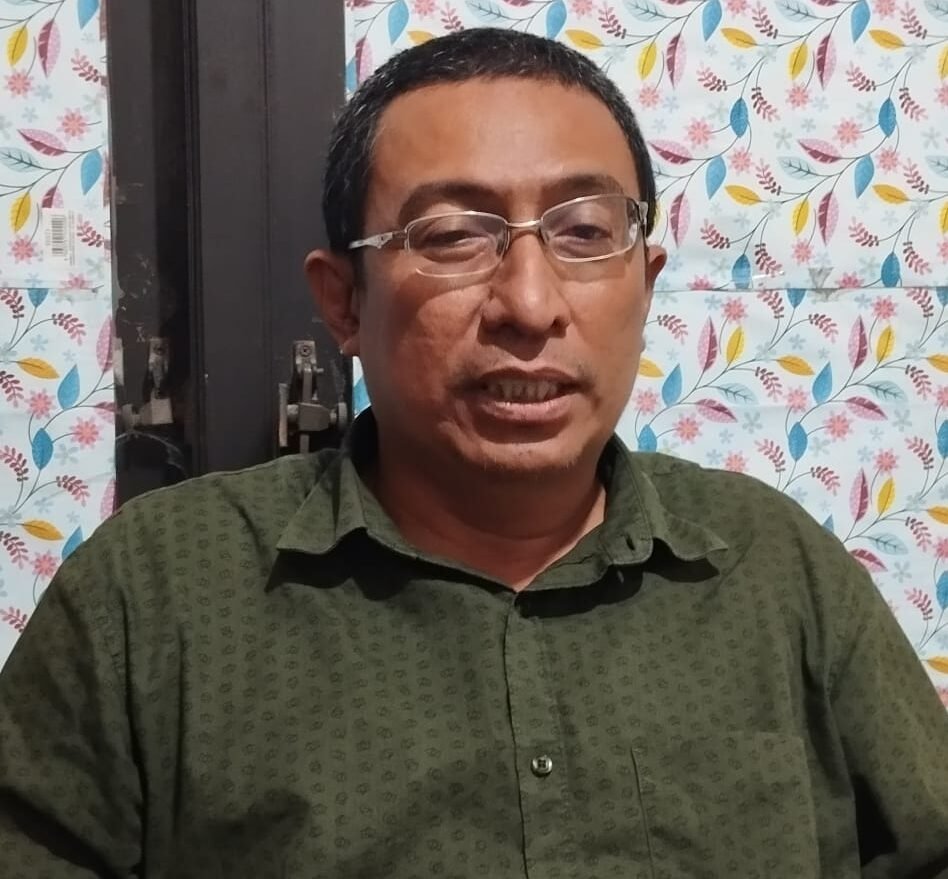ESAI BUDAYA
OLEH YULIANTORO
Ada perjalanan-perjalanan yang tidak pernah selesai meski rutenya sudah lama ditutup waktu. Ia hanya berhenti sebentar di tikungan ingatan—seperti bus malam yang menepi di terminal kecil—lalu berjalan lagi setiap kali deru mesin, bau solar, atau denting pintu besi memanggil kenangan lama yang kita kira sudah padam.
Bagi banyak orang, bus hanyalah alat transportasi. Tapi bagiku, Sumber Kencono—yang sekarang dikenal sebagai Sugeng Rahayu—adalah saksi hidup dari sebuah masa ketika mimpi dibangun tanpa rumus, hanya dengan doa, keberanian, dan sedikit keberuntungan.
Dan Sabtu pagi, 15 November 2025, setelah lima belas tahun tidak menyentuh kursinya, aku kembali menapaki tangga bus itu. Perjalanan kecil yang terasa seperti menyalami diriku sendiri di masa muda.
Aku kembali pada tahun 1997, usia masih hijau, mental masih bolong-bolong seperti karcis bus yang disobek separuh. Suatu hari datang sepucuk surat panggilan kerja dari Solo—pendek, tegas, dan mengubah jalan hidupku.
Aku belum tahu perusahaan apa yang memanggilku. Aku tidak kenal bosnya. Dunia liputan pun masih gelap. Yang kutahu hanya satu: 1 Maret, aku harus datang mengikuti pelatihan jurnalistik di Stadion Manahan.
Karena pelatihan itu berlangsung sebulan penuh, aku otomatis menjadi penyebrang harian Jogja–Solo. Dari situlah persahabatanku dengan bus Sumber Kencono (SK) dimulai.
SK bukan sekadar angkutan. Ia seperti guru keras yang tak menerima alasan: disiplin, cepat, tepat waktu. Tahun 1997, tarifnya 450 rupiah. Kondektur tidak pernah menaikkan harga sesuka hati. Jadwal berangkat tetap berjalan meski kursi masih longgar. Jika bukan SK, aku naik Mira Eka—dua “pasukan cepat” masa mudaku.